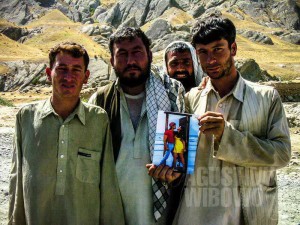Selimut Debu 86: Hari Massoud
Orang mengingatkanku untuk selalu berhati-hati dengan perbatasan Iran dengan Afghanistan, karena pemeriksaan bisa sangat panjang. Ya, Iran selalu khawatir dengan tetangganya yang lucu ini, yang selalu dicurigai sebagai pemasok opium dan pengungsi. Tapi tidak demikian dengan sebaliknya bukan? Aku rasa, karena aku menyeberang dari Iran ke Afghanistan, seharusnya semua berjalan lancar. Benar saja. Semua lancar. Malah terlalu lancar. Aku tidak pernah melihat imigrasi perbatasan yang selonggar imigrasi Afghanistan ini. Aku sudah menyodorkan pasporku tepat di halaman visa, sehingga si petugas Afghan tinggal mengecap. Petugas itu langsung mengecap, tanpa menghabiskan sedetik pun untuk melihat visa itu, melihat halaman depannya, atau bahkan untuk melihat wajahku. Tanpa registrasi, tanpa wawancara, tanpa rewel. Proses imigrasi hanya memakan waktu 3 detik. Ini adalah proses yang paling cepat dan efisien yang kualami. Dan berita gembira lainnya, tidak ada pula pemeriksaan barang di bea cukai. Datang dari Iran, kita semua dianggap sebagai makhluk tak berdosa. Meninggalkan gerbang perbatasan Islam Qala, aku seperti masuk ke mesin waktu lagi, meloncati dimensi waktu dan mundur ke masa lalu, dari modernitas kembali ke realita negeri berselimut debu. Debu, dalam artian harfiah, lekat dengan kehidupan penduduk Herat. Di bagian timur kota ini, hingga ke perbatasan Iran, terbentang gurun pasir luas. Selama 120 [...]