Pulau Strachan 25 Agustus 2014: Sejarah Berdarah

Satu malam di Pulau Strachan (AGUSTINUS WIBOWO)
Langit belum gelap. Tais tujuan kami masih kurang sedikit lagi. Tetapi Sisi dan para lelaki di perahu kami memutuskan untuk menghentikan perjalanan ini.
“Tapi, kenapa?” Saya bertanya, sembari membayangkan bagaimana beratnya malam ini yang akan kami lewatkan di tengah hutan kosong, di alam terbuka. Ini gara-gara kami berangkat sangat terlambat meninggalkan Ber, karena harus menunggu Sisi dan Marcella balik dari Boigu, sehingga perjalanan kami molor hingga sore hari. Laut sebenarnya tidak seganas kemarin, saya mulai menikmati perjalanan ini walaupun punggung saya masih ngilu setiap kali perahu kami menghentak-hentak di atas ombak. Saya percaya, sebenarnya kami bisa mencapai Tais, yang jaraknya cuma 30 kilometer, malam ini juga.
“Itu karena kamu orang putih,” kata Sisi, “Kami semua harus menghormati kamu, jadi kami tidak akan bepergian dalam gelap.”
“Tapi aku lebih nyaman jika kita malam ini tidur di desa.”
“Kami orang hitam tidak masalah kalau bepergian dalam gelap, tapi kamu orang putih takkan bisa.”
Saya tidak tahu apakah ada bedanya. Dalam perjalanan ini, saya cuma penumpang, yang hanya duduk manis di dalam perahu tanpa membantu mereka apa-apa; pergi pagi atau malam mestinya kehadiran saya tak berpengaruh bagi mereka. Kemisteriusan Sisi bersama kawan-kawannya itulah yang justru menambah ketakutan saya. Marcella tidak ikut dalam perjalanan menuju Tais ini, tinggal di Buzi dan menunggu di sana hingga kami pulang nanti. Sekarang semua penumpang perahu, selain saya, adalah orang Tais. Tais adalah sebuah desa di Distrik Morehead. Dan apakah itu More Head? Apakah itu berarti mereka butuh kepala lebih banyak? Mark si pemuda Tais berkulit paling legam di antara mereka, mengingatkan saya bahwa daerah ini penuh sihir hitam yang sangat kuat dan kejam, seperti halnya hujan lebat dan badai dahsyat yang menghantam kami saat berangkat dari Daru beberapa hari lalu, karena seorang lelaki tua penyihir yang mau berhubungan seks dan ditolak sehingga marah dan memanggil badai. Langit mulai meremang, saya merasakan bulu kuduk saya merinding hebat.

Perjalanan meninggalkan Ber, melintasi laut yang selalu marah (AGUSTINUS WIBOWO)

Di daerah ini, beberapa puluh tahun lalu, masih terjadi pembunuhan untuk perburuan kepala (AGUSTINUS WIBOWO)
Kami merapat di pesisir pantai gelap. Kami melihat ada perahu lain yang bersandar di pantai. Ada manusia di tanah kosong ini! Sisi meminta saya untuk tidak bersuara apa-apa. Mereka berteriak-teriak dalam bahasa daerah, untuk memastikan apakah manusia yang ada di sana adalah wantok—orang satu bahasa yang berarti kawan, ataukah lawan. “Kita harus sangat berhati-hati,” kata Sisi, “Di sini orang bisa membunuhmu kalau kamu tidak menurut aturanku.”
Saya selalu memprotes Sisi yang sejak meninggalkan Daru melarang saya untuk mengatakan kepada orang-orang—kecuali apabila dia sudah mengizinkan—bahwa saya berasal dari Indonesia. Dia telah menciptakan sebuah identitas bagi saya: orang Filipina yang bekerja di supermarket China di Daru. “Mengapa?” selalu saya tanyakan. Sisi menjawab, “Karena orang-orang ini selalu dengki. Mereka bisa menyakitimu, bahkan membunuhmu.”
Musafir yang tinggal di tanah kosong ini ternyata adalah sesama orang Tais. Dari atas tebing kecil di dekat pantai, mereka menyorotkan senter ke arah kami, membantu kami naik menapaki tebing itu. Mereka adalah rombongan keluarga yang mengantar satu lelaki muda, yang mengalami luka di kaki sehingga harus berjalan dengan tongkat, rencananya akan pergi berobat di rumah sakit di Daru. Mesin perahu mereka rusak, sehingga mereka terdampar di tanah kosong ini.
Tebing ini adalah awal dari Pulau Strachan, sebuah tanah datar berbentuk kotak yang lebar timur ke barat 16 kilometer dan panjang utara ke selatan 29 kilometer. Pulau Strachan sebenarnya bukan pulau sungguhan, tetapi seperti pulau karena diapit dua sungai besar penuh buaya: Mai Kassa dan Wasi Kussa. Kedua sungai ini pun bukan sungai sungguhan, karena merupakan perpanjangan dari laut yang menjorok ke daratan dan berair asin hingga berkilometer.
Kami mengumpulkan kayu bakar, membuat api unggun di tepi tiang-tiang kayu bekas bangunan rumah, di atas tanah datar yang diselimuti daun-daun kering menguning. Para lelaki muda juga membuat api unggun lain yang lebih besar, bersama mereka mengobrol dalam bahasa daerah yang saya sedikit pun tak bisa mengerti. Sisi mengeringkan baju-baju saya, membersihkan kerikil dari tanah yang akan mengalasi tidur saya malam ini. Pelayanannya dan perhatiannya bagi saya terasa begitu berlebihan.

Pulau Strachan (sumber: wikimapia)

Tais semula adalah desa pesisir (AGUSTINUS WIBOWO)

Kami melewatkan malam bersama di alam terbuka (AGUSTINUS WIBOWO)
“Dulu,” kata Sisi sambil duduk di hadapan api unggun, “desa Tais terletak di pesisir Pulau Strachan sini. Tetapi mereka semua pindah karena terjadi pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh para pemburu kepala.”
Para pemburu kepala itu datang dari pedalaman Pulau Strachan, dari pedalaman Morehead, juga jauh dari barat pada Papua sisi Belanda (sekarang Indonesia). Para pemburu kepala zaman itu itu menggunakan sihir yang membuat orang menjadi gila, lalu membunuhi mereka untuk diambil tengkoraknya. Pembunuhan itu membuat orang Tais melarikan diri dan pindah ke desa pedalaman, jauh dari pantai.
Sisi tidak tahu pasti, kapan itu terjadi. Mungkin seratus tahun lalu? Dua ratus tahun lalu? Zaman itu, penduduk Tais tinggal di pesisir yang lebih dekat dari Boigu, sering menyeberang ke pulau itu untuk berdagang barter dengan ketela dan pisang mereka. Daerah pesisir ini sering dilanda pasang besar. Penduduk bisa berenang, tetapi hewan mereka mati semua dan rumah mereka hancur. Itu sebabnya mereka pindah ke sisi Pulau Strachan yang ini, di atas tebing.
Seorang lelaki tua Tais menjelaskan pada saya, perpindahan karena pembunuhan magis itu terjadi pada masa Perang Dunia II, karena dia ingat waktu itu melintas pesawat perang di angkasa, orang-orang tidak pernah melihat pesawat sangat ketakutan sehingga bersembunyi di bawah pohon kelapa atau meringkuk di dalam rumah. Orang-orang waktu itu sangat takut melihat orang putih, karena dikira setan. Orang Pulau Strachan waktu itu membunuh seorang putih berdasi yang membawa kitab, lonceng, dan Kabar Baik (bahwa para orang hitam itu juga akan diselamatkan oleh Yesus). Sebelum Kristen masuk, kultur berburu kepala adalah tradisi sini untuk menghormati kaum perempuan. Para perempuan akan menaruh kepala-kepala yang sudah dipotong ke dalam keranjang, lalu menari dengan kepala-kepala itu.
Dulu, leluhur mereka tidak tinggal di rumah panggung, melainkan di rumah panjang tepat di atas tanah, dikelilingi dinding bambu. Mereka sekeluarga berssembunyi di dalam rumah ketika para pemburu kepala itu datang. Para pemburu kepala akan melontarkan tombak dari luar. Sedangkan dari dalam rumah, dari celah bilah-bilah bambu, penghuni yang diserang akan memanah ke luar ke arah para pemburu itu.

Masa lalu berdarah itu sebenarnya masih belum lama berlalu (AGUSTINUS WIBOWO)
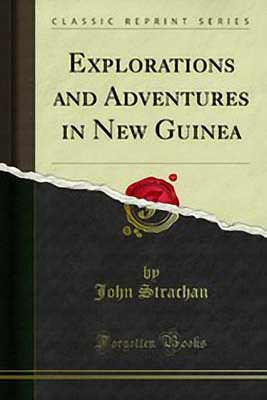
Explorations and Adventures in New Guinea, by John Strachan
Morehead memang sesuai namanya. Di daerah ini hingga beberapa dekade lalu masih marak kultur perburuan kepala. Mereka membunuh musuh dan mengoleksi tengkoraknya di rumah panjang mereka. Semakin banyak kepala yang kau punya, semakin besar pula kekuatanmu. Konon, para pejabat kolonial dari Inggris dan Australia mengunjungi rumah-rumah panjang sebelum mereka menghancurkannya, dan mereka sangat terkejut menemukan bahwa di daerah ini rumah-rumah panjang memiliki jauh lebih banyak tengkorak daripada di daerah lain. Much more heads. Begitulah daerah ini mendapat namanya: Morehead.
Nama-nama peninggalan kolonialisme itu, walaupun sangat merendahkan martabat seolah mereka adalah bangsa barbar yang harus ditemukan dan dicerahkan oleh Barat, tetap dipakai hingga sekarang setelah Papua Nugini merdeka begitu lama. Seperti ibukota mereka yang bernama Port Moresby, karena “ditemukan” oleh seorang eksplorer Barat bernama Moresby, “pulau” ini pun berasal dari nama seorang eksplorer Barat bernama John Strachan, yang menjelajah daerah ini pada tahun 1884.
Dalam bukunya Explorations and Adventures in New Guinea, Strachan menulis bahwa dia membawa barang untuk ditukar dalam jumlah besar: kapak, pisau panjang, kampak tomahawk, pipa, tembakau, manik-manik, kain dan sapu tangan. Dia menjanjikan, sebagai orang putih dia akan melindungi mereka orang Kamara dari orang-orang Tugara musuh mereka. Dan sebagai imbalan dari barang-barang yang dibawanya dan perlindungannya itu, Strachan bertanya pada kepala suku, “Apakah kalian bersedia saya datang dan menguasai pulau ini? Semua orang tetap memiliki kebunnya masing-masing, dan untuk semua tanah yang tidak dipakai apakah kalian bersedia untuk memberikan pada saya?” Semua orang menyatakan setuju, dan John Strachan memberitahu mereka bahwa nama tempat ini adalah “Pulau Strachan”. Sejak saat itu penduduk pribumi mengetahui nama pulau yang mereka tinggali.
Strachan bagi saya adalah sosok penjajah dalam artian sebenarnya, yang dalam superioritasnya sebagai eksplorer yang merambah daerah-daerah tak dikenal lalu memanipulasi dan menindas suku-suku yang masih primitif. Dia menyusuri sungai untuk mengelilingi “pulau” ini, dan membunuh banyak penduduk pribumi. Dia bahkan membuat torpedo dari batang timah, yang diisi 25 pon bubuk mesiu, dan diledakkan dari jarak setengah mil—untuk menyerang dan menakuti penduduk pribumi.
Strachan juga mendeskripsikan tentang pembunuhan yang didengarnya, dilakukan oleh orang-orang Pulau Strachan yang haus darah terhadap desa di Boigu. Seribuan orang mengepung desa, lalu membantai laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sekitar 30 dari 350 penduduk berhasil melarikan diri ke rawa. Sedangkan yang masih hidup dan tertangkap, mereka ikat di kano. Para penakluk itu kemudian membuat api dan mulai berpesta dengan daging orang-orang yang terbunuh. Mereka terus berpesta selama berhari-hari, bernyanyi dan menari dengan keriangan iblis sampai mereka memakan habis korban yang terbunuh dalam pertarungan itu. Ketika mereka menemukan kaki dari korban mereka membengkak karena jeratan tali yang mengikat, dan tampaknya mereka akan mati hanya dari sakit yang tak terperi, maka para penyerang itu akan memotong tali dan menggunakan tongkat untuk memukuli kaki itu hingga hancur. Dari korban yang masih hidup itu, mereka akan memotong dagingnya, yang akan mereka panggang dan mereka santap tepat di hadapan mata si korban malang—yang sedang menggeliat kesakitan menantikan saat diirisnya sisa tubuh mereka dan datangnya kematian yang akan mengakhiri penderitaan mereka.
Strachan meyakini deskripsi ini semua benar adanya, dan ketika dia mencatat ini dia pun merasakan darah bergejolak dalam tubuhnya karena berpikir:
“Kami, orang-orang dari negeri merdeka mengirim misionaris dengan Alkitab di satu tangan untuk mewartakan bahwa “Tuhan adalah kasih”,… bahwa ada perdamaian dan keamanan di dalam Kristus; untuk mengajari mereka menghancurkan panah dan tombak mereka, untuk hidup dalam harmoni dengan sesama mereka. Tetapi, dengan membiarkan kebarbaran kanibal ini untuk hidup dalam simpati dan kepercayaan kekanak-kanakan, kita tidak sedikit pun melindungi mereka dari para setan [pembunuh] itu. … Tidak satu pun dari kapal perang kita yang digunakan, tidak satu penny pun dari 50.000 poundsterling dana kita yang dipakai, untuk melindungi para saudara sesama Kristen kita di Barat!”
Dan itulah yang menjadi apologi dari Strachan untuk melakukan pembantaian terhadap orang-orang di New Guinea ini. Demi melindungi hak orang-orang putih seperti dirinya. Dan itulah mentalitas para kolonialis Barat: bahwa Timur perlu orang-orang seperti mereka untuk menjinakkan dan membawa pada peradaban. Mereka menjajah untuk mencerdaskan dan memberi pencerahan pada kami. Betapa mulia! Warga lokal pun, tidak pernah mengetahui sekejam apa sebenarnya leluhur mereka, karena sejarah mereka hanyalah kisah dari mulut ke mulut, sedangkan bukti otentik deskripsi sejarah mereka pun ditulis oleh tangan orang asing, yang berleluasa untuk memodifikasi sejarah bangsa-bangsa taklukannya sesuka mereka. Di sisi lain, memang harus diakui, kedatangan misionaris di daerah Papua Nugini ini memang punya peranan menghentikan kultur perburuan kepala secara mendadak, walaupun juga sekaligus menghentikan banyak kultur leluhur mereka yang lain—yang akan saya temukan dalam perjalanan saya berikutnya di negeri ini.

Perburuan kepala berhubungan dengan kanibalisme dan kekurangan makanan (AGUSTINUS WIBOWO)

Hidup di hutan rimba Papua Nugini membutuhkan fisik yang sangat tangguh (AGUSTINUS WIBOWO)
Dalam buku Savage Harvest karya jurnalis Carl Hoffman tentang kultur kanibalisme di Asmat, Papua, penulis berargumentasi bahwa kultur perburuan kepala tidak terlepas dengan kanibalisme dan kekurangan makanan. Awalnya, daerah yang tanahnya miskin memaksa penghuninya untuk membunuh manusia lain untuk memenuhi kebutuhan protein mereka sehingga tetap bertahan hidup. Kemudian itu dikuatkan dengan spiritualisme, dengan dewa-dewa dan keterjaminan masa depan, sehingga perburuan kepala menjadi tradisi yang berlangsung turun-temurun; di banyak tempat itu adalah tradisi yang menandai inisiasi kedewasaan seorang lelaki.
Sebenarnya, kultur berburu kepala manusia bukan hanya ada di pulau Papua (Pulau New Guinea) ini, tetapi juga di banyak pulau-pulau lain yang sekarang menjadi Indonesia. Eksplorer Italia Elio Modigliani mengunjungi masyarakat pemburu kepala di Nias Selatan pada tahun 1886, dan menemukan bahwa tujuan memiliki tengkorak korban adalah kepercayaan bahwa si korban akan melayani sebagai budak dari pemiliknya pada kehidupan sesudah mati nanti, sehingga tengkorak manusia menjadi barang komoditas berharga. Saya pernah membaca catatan eksplorer Prancis (Orang Indonesia & Orang Prancis dari Abad XVI sampai dengan Abad XX) bahwa di kalangan masyarakat Batak abad ke-19 masih berlangsung tradisi membunuh orangtua mereka sendiri yang sudah renta untuk dimakan. Di Sumba, perburuan kepala masih berlangsung hingga awal abad ke-20 dalam perang-perang antar suku, dan tengkorak korbannya dikumpulkan untuk digantungkan di sebuah pohon tengkorak di tengah desa. Di tahun 2001, ketika terjadi konflik rasial di Sampit, Kalimantan, juga terjadi pemenggalan kepala atas korban Madura oleh orang Dayak–peristiwa dengan konteks sosial politik di zaman modern yang membangkitkan memori ritual perburuan kepala di masa lampau, juga kepercayaan bahwa jika mereka memakan hati musuh maka roh korban tak akan mengganggu seumur hidup. Sejarah itu masih belum terlalu lama. Masih lekat dalam ingatan saya bagaimana gambar-gambar seram barisan kepala manusia berjajar masih bersimbah darah, di Indonesia negeri saya sendiri, bertebaran di internet, sementara berbagai penjuru dunia lain merayakan kemajuan teknologi informasi digital yang menandai abad milenium. Dan di Papua Nugini, dengan mereka sendiri memiliki sejarah perburuan kepala, tak heran begitu banyak orang memercayai rumor bahwa kini orang Indonesia berdatangan ke Daru untuk membunuhi mereka dan membawa tengkoraknya untuk membangun gedung dan jembatan di Merauke.
Malam semakin larut. Saya meringkuk di atas terpal pembungkus kargo di perahu yang kini berfungsi sebagai alas tidur saya di tanah berkerikil menusuk-nusuk. Api bergemeretak melalap ranting pohon yang terus disuapkan Sisi sepanjang malam, untuk menghangatkan tubuh saya. Di api unggun sebelah, terdengar teriakan riang para pemuda. Mereka berhasil membunuh seekor ular piton sepanjang tiga meter. Mereka memanggang ular itu di atas api, dan bersama bersantap penuh riang di tengah malam.

Pulau Strachan (AGUSTINUS WIBOWO)






mas agus sy klarifikasi sdkt perburuan kpl oleh orang dayak sdh d hentikn hmpir seratus th yg lalu melalui prnjanjian tumbang anoi yg d fasilitasi raja putih sedngkn historis peristiwa sampit lbh d latarbelakangi olh gesekan sosial politik akibt kebijakan migrasi yg memprsempit ruang hidup msyarkt asli..karakteristik pndatang yg tk mnjunjung tinggi adab lokal sdh d tahan sebisa mngkin smp akhirny dayak tdk pny pilihn lain selain bertindak komunal dg cara yg mereka tw utk menyatakan bhw mereka masih eksis d tk bisa d tindas seenak perut..jd agak brbeda situasiny..tp tulisan ini menarik dn sy suka skl
Nina Aja Terima kasih Nina untuk konfirmasinya. Maksud saya adalah bagaimana tradisi headhunting yang sudah lenyap seratus tahun lalu itu bisa muncul lagi dalam konteks konflik di era modern. kenyataannya memang headhunting saat ini tidak selalu berhubungan dengan kanibalisme (seperti halnya di konflik2 yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia di awal abad ini), tetapi tradisinya sendiri sangat mungkin berhubungan dengan kanibalisme di masa lampau.
iya..mekanisme pertahanan dr yg muncul scr spontan krn desakn dr luar yg sdh tk trtahankn lg
Nina Aja Terima kasih untuk masukannya. sudah saya edit sedikit kalimat bagian itu untuk memperjelas 🙂
aduh..jd gk enak..hehehe…makasih mas agus..sukses sll
jadi ingat peristiwa “petrus” thn 1980an. orang (yg dianggap perusuh/preman) ditembak dimasukkan karung lalu dibuang ke sawah (tuang)
di kampungku ada 3-4 peristiwa penemuan “mayat dlm karung”. satu diantaranya dikubur di pemakaman kampungku. aku yg saat itu msh SD (dan di kampung blm ada PLN), rasanya seremmm menakutkan. apalagi dibumbui cerita bhw mayatnya diberi perasan jeruk nipis dan bakal jd hantu. bener2 serammm
Salut risetnya. Empat jempol!
Membaca tulisan ini, saya merasakan sejarah perburuan kepala itu begitu dekat. Seakan belum lama terjadi. Di balik bentangan alam yang indah, ternyata menciptakan kultur yang mengerikan. Tentu tak mudah jika saya pun berada dalam posisi mereka.
dari dulu pengen sekali menginjakkan kaki di tanah papua nugini agus, u keren dah udh kesana
Pengalaman dik agus sangat langka..buat iri tiap petualang …salut buat anda! Di tunggu cerita hebat terbaru nya…
Cerita dan sejarah dari pulau yang punya banyak sejarah mengerikan, makasih mas sudah sharing dari pedalaman papua