Cina, China, atau Tiongkok?

Saya dibesarkan untuk membenci kata “Cina”.
Orangtua mengajarkan kami untuk menyebut negeri leluhur itu dengan nama terhormat Chung Kuo (Tiongkok). Mereka bahkan tidak segan menampar saya apabila saya sampai berani menyebut kata “Cina” di rumah.
Kata “Cina” bagi saya memang membangkitkan trauma. Saat masih kecil dulu, saya sering diolok-olok para bocah di gang belakang, “Cina! Cina sipit! Pulang ke negaramu sana!” Sering pula saya dimintai duit hanya karena saya Cina. Semakin saya beranjak dewasa, sirene alarm dalam otak saya berdering semakin nyaring setiap kali mendengar kata itu diucapkan.
Tetapi kemudian, saya menemukan satu keanehan. Sebagai kolektor prangko, saya mendapati semua prangko yang diterbitkan Cina pasca tahun 1992 mencantumkan nama negara dalam bahasa Inggris: CHINA. Saya tidak habis pikir. Kalau nama “Cina” itu benar-benar hina, mengapa mereka yang di sana justru bangga menyebut diri sebagai “China”? Bukankah “Cina” dan “China” itu seharusnya sama saja?
Di Indonesia pasca Reformasi 1998, penyebutan nama negara Cina dan orang-orang keturunan Cina menjadi perkara sensitif. Media-media resmi pun tampaknya kebingungan. Ada yang masih tetap memakai “Cina”. Ada yang memakai ejaan bahasa Inggris “China”, yang dibaca dengan pelafalan bahasa Inggris Chai-na. Ada pula yang kukuh menggunakan “Tiongkok” dan “Tionghoa”.
Mengapa menyebut nama sebuah negara saja bisa begini ribet?
Nama negara itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama adalah endonim (“nama dalam”), yaitu nama yang dipakai oleh orang-orang di negara itu untuk menyebut negaranya sendiri. Dan yang kedua adalah eksonim (“nama luar”), nama yang digunakan oleh orang luar untuk menyebut negara itu. Dalam kebanyakan kasus, endonim dan eksonim ini adalah sama. Misalnya Indonesia. Orang Indonesia menyebut negaranya sendiri sebagai “Indonesia”, dan orang asing juga sama menyebutnya sebagai “Indonesia”.
Namun ada pula negara yang endonim dan eksonimnya berbeda. Misalnya orang Yunani menyebut negara mereka sebagai Hellas. Orang India menyebut negaranya sendiri sebagai Bharat. Sedangkan orang Korea menyebut tanah air mereka sebagai Choson (di Korea Utara) atau Hanguk (di Korea Selatan). Cina juga termasuk dalam kelompok ini. Orang Cina menyebut negara mereka sendiri sebagai Zhongguo (dibaca Chung Kuo), sangat berbeda dengan nama resmi “China” yang dipakai di forum internasional.
Eksonim “China” itu, menurut penjelasan yang paling umum, adalah berasal dari nama Dinasti Qin (baca: Ch’in), yang pertama kali mempersatukan negeri Cina pada abad ke-3 SM. Penyebutan nama ini yang paling awal diketahui adalah dalam bahasa Sanskerta India, yaitu चीन (Cīna), sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mahabharata dan Arthasashtra. Nama ini menyebar ke barat, diserap ke dalam bahasa Persia Kuno sebagai Čīn, dan ke dalam bahasa Latin sebagai Sina. Kata bahasa Latin ini adalah sumber bagi nama Cina dalam kebanyakan bahasa Eropa, termasuk “China” dalam bahasa Inggris. Kemudian, di masa perdagangan Jalur Sutra, Cina dikenal karena produk keramiknya, sehingga kata china dalam bahasa Inggris juga berarti “keramik”.

Sementara itu, nama yang digunakan orang Cina untuk menyebut negeri mereka dalam bahasa mereka sendiri adalah 中國 Zhongguo. Di Indonesia nama ini dilafalkan sebagai “Tiongkok” menurut dialek Hokkian di Cina Selatan. Ini adalah nama sakral yang dipegang teguh oleh banyak orang Tionghoa di Indonesia. Namun tidak banyak orang Tionghoa yang menyadari—bahkan tidak banyak pula orang Cina di Tiongkok sana yang mengetahui—bahwa Zhongguo atau Tiongkok itu bukanlah nama permanen negeri Cina sejak dahulu kala.
Nama resmi negara Cina sebenarnya berubah-ubah sesuai dengan nama dinasti apa yang berkuasa. Ketika Dinasti Han yang berkuasa, maka nama negara Cina adalah “Han”. Ketika Dinasti Tang berkuasa, maka namanya adalah Tang. Di masa Dinasti Ming, namanya adalah Da Ming (“Ming Raya”), dan di masa Dinasti Qing namanya menjadi Da Qing (“Qing Raya”). Itulah nama yang tertulis pada panji-panji perang dan dokumen-dokumen resmi kekaisaran.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Cina, tetapi merupakan fenomena umum di berbagai penjuru dunia. Sebelum merebaknya era nasionalisme pada abad ke-19, belum ada kepentingan mendesak bagi negara-negara di dunia untuk memiliki nama resmi yang unik dan permanen. Nama negara-negara dunia pada masa pra-nasionalisme umumnya ditentukan oleh nama dinasti atau keluarga para penguasanya.
Penggunaan nama dinasti sebagai nama negara juga lazim di kalangan rakyat jelata. Berbeda dengan orang luar yang mengidentikkan Cina dengan Dinasti Qin, orang Cina di Tiongkok mengidentifikasi diri dengan Dinasti Han (202 SM – 220 M), sehingga menyebut diri sebagai Hanren (“orang Han”) dan menyebut bahasa Mandarin mereka sebagai Hanyu (“bahasa Han”). Sementara para perantau Cina di luar negeri justru mengidentifikasi diri dengan Dinasti Tang (618 – 907 M), dan menyebut diri sebagai Tangren (“orang Tang”, yang di Indonesia dilafalkan sebagai Tenglang).

Sedangkan Zhongguo adalah nama negeri Cina yang tidak berkorelasi dengan nama dinasti penguasa. Nama ini sudah berusia tiga ribu tahun, pertama kali digunakan pada masa Dinasti Zhou Barat (1045 – 771 SM). Nama ini terdiri atas dua aksara, yaitu 中 zhong yang berarti “tengah” atau “pusat”, dan 國 guo yang berarti “negara”, sehingga Tiongkok sering diartikan sebagai “negara tengah”, “negara pusat”, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Middle Kingdom.
Tetapi makna semula dari nama ini bukanlah keseluruhan negara Cina sebagaimana yang kita kenal sekarang. Sebelum masa penyatuan Cina oleh Dinasti Qin, istilah Zhongguo itu digunakan untuk menyebut sejumlah negeri yang terletak di Dataran Tengah Cina, yang merupakan pusat kebudayaan unik di sekitar Lembah Sungai Kuning. Demikian pula pada masa Dinasti Han, Zhongguo itu merujuk pada daerah-daerah pusat peradaban yang terbatas pada Cina bagian tengah. Pada dinasti-dinasti berikutnya, kata ini merujuk pada wilayah pusat atau wilayah utama kekuasaan kaisar. Dengan demikian, Zhongguo secara geografis jauh lebih kecil daripada wilayah keseluruhan negara Cina sekarang.
Selain Zhongguo, sebenarnya masih banyak lagi nama lainnya yang pernah digunakan orang Cina sepanjang sejarah untuk menyebut negeri mereka. Yang paling sering adalah Tianxia, secara harfiah berarti “di bawah langit”, yang artinya adalah semua wilayah yang tunduk di bawah kaisar Cina sebagai pemegang mandat Kaisar Langit. Ada juga Zhonghua, yang di Indonesia dilafalkan sebagai “Tionghoa”, sebenarnya adalah sinonim dari Tiongkok. Nama lain yang cukup populer adalah Huaxia, yang berasal dari Dinasti Xia yang sangat kuno.
Barulah pada akhir abad ke-19, istilah Zhongguo mulai sering dipakai secara informal untuk menyebut negeri Cina. Ini adalah masa pemerintahan Dinasti Qing, yang didirikan pada tahun 1644 M oleh bangsa Manchu yang berasal dari daerah Manchuria di timur-laut Cina. Pada saat inilah terjadi perluasan makna Zhongguo. Kata itu bukan hanya merujuk pada Dataran Tengah yang dihuni orang Cina Han saja, tetapi juga seluruh wilayah taklukan kekaisaran Qing, yang termasuk Manchuria, Mongolia, Xinjiang, dan Tibet. Wilayah Qing pada masa itu bahkan masih lebih luas daripada wilayah RRC modern.

Awal abad ke-20 adalah fajar ideologi nasionalisme bagi banyak bangsa Asia. Para aktivis nasionalis di Cina meratapi nasib negeri mereka yang bobrok di bawah Qing, yang mereka pandang sebagai bangsa asing yang menjajah tanah air mereka. Ketika negara-negara Eropa sudah punya nama masing-masing, orang Cina masih harus menyebut negeri mereka dengan nama dinasti yang mereka benci, “Qing”. Para tokoh nasionalis Cina kemudian sepakat bahwa negara dan bangsa mereka harus punya nama baru yang permanen. Ada beberapa nama yang dipertimbangkan, dan yang akhirnya dipilih adalah Zhonghua dan Zhongguo. Setelah Dinasti Qing ditumbangkan pada tahun 1912, nama resmi negara Cina yang didirikan kaum nasionalis adalah Zhonghua Minguo (secara harfiah: “Republik Tionghoa”), yang disingkat Zhongguo.
Ini menandai lahirnya bangsa Cina modern. Nama negara dan bangsa ini membawa kebanggaan baru bagi orang Cina di seluruh dunia. Nama Zhongguo yang semula hanya bermakna geografis, kini telah mendapatkan pemaknaan baru yang menyiratkan superioritas bangsa. “Negeri-negeri tengah” kini bisa dimaknai sebagai “negara pusat”: pusat peradaban, pusat dunia. Penggunaan nama kuno yang mendapatkan pemaknaan baru adalah hal yang lazim dalam proses penamaan negara-negara dan bangsa-bangsa modern. Sama seperti Zhongguo, endonim “Nusantara” yang sempat diusulkan untuk menamai Indonesia pada awal abad ke-20, juga telah mengalami pergeseran makna yang cukup jauh dari makna aslinya di zaman Majapahit.
Keberhasilan gerakan nasionalis di Cina yang mendirikan republik modern juga membawa kebanggaan luar biasa bagi orang-orang Cina di Indonesia. Pada saat itu, gerakan nasionalisme di Indonesia masih baru bersemi; negara dan bangsa Indonesia bahkan masih belum punya nama. Sebaliknya, orang Cina di Indonesia sudah bisa dengan bangganya menyebut negeri asal mereka sebagai “Tiongkok”, dan bangsa mereka sebagai “Tionghoa”.
Tetapi jauh sebelum digunakannya nama “Tiongkok” dan “Tionghoa” itu, di Indonesia sudah ada nama “Cina”. Kita bisa melihat ini pada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang mengandung “cina”, seperti misalnya pacar cina, petai cina, dan pecinan. Semua kosakata ini bersifat netral, tidak mengandung unsur penghinaan apa pun. Kita tidak pernah menyebut pacar Tiongkok, petai Tiongkok, atau petiongkokan.

Seiring waktu, kata “Tiongkok” dan “Tionghoa” pun menggeser penggunaan kata “Cina” dalam konteks formal di Indonesia, juga dianggap merupakan penyebutan yang lebih sopan. Semasa pemerintahan Presiden Sukarno, ketika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina sangat erat, nama resmi negara itu dalam bahasa Indonesia adalah “Tiongkok”.
Namun keadaan ini berubah pada masa Orde Baru Suharto, yang mengusung narasi anti-komunis dan anti-Cina. Pemerintah Suharto menerbitkan aturan khusus yang melarang penggunaan kata “Tiongkok” dan “Tionghoa”, dan mengembalikannya menjadi “Cina”. Menurut pejabat Indonesia pada waktu itu, tujuan aturan ini adalah untuk “menghapuskan perasaan inferior pada orang kita, dan di lain pihak menghapus perasaan superior pada golongan yang bersangkutan dalam negara kita”.
Di samping itu, banyak sekali aturan diskriminatif lain yang diterbitkan pada masa Orde Baru yang dikhususkan bagi warga keturunan Cina di Indonesia. Mereka tidak boleh menyandang nama Cina, tidak boleh belajar dan bicara bahasa Cina, tidak boleh menjalankan tradisi Cina secara terbuka, atau tidak boleh menganut agama tradisional Cina.
Saya bertumbuh di periode akhir Orde Baru, dan merasakan betapa semua aturan itu sungguh berpengaruh besar untuk membuat saya malu untuk menjadi Cina, malu dengan identitas kecinaan saya sendiri. Karena itu saya bisa memahami mengapa banyak orang Tionghoa di Indonesia, terutama generasi orang tua yang merasakan langsung pahitnya diskriminasi sepanjang era Orde Baru, sangat sensitif dengan kata “Cina”, dan tidak pernah sudi dipanggil “Cina”.
Tetapi kebanyakan orang Tionghoa Indonesia, terutama yang totok, lebih sering mengaitkan antipati mereka terhadap kata “Cina” itu dengan kata 支那 Zhina yang digunakan oleh Jepang untuk menyebut Cina. Kata itu memang mirip sekali pelafalannya dengan kata “Cina” dalam bahasa Indonesia, dan itu menjadi alasan penolakan mereka terhadap kata “Cina” yang dipaksakan oleh rezim Suharto. Di Tiongkok sana, kata itu memang membangkitkan trauma mendalam. Pada masa Perang Dunia II, Jepang sering menghina Zhina sebagai “Si Penyakitan dari Timur”.

Sebenarnya kata Zhina bukan diciptakan oleh Jepang. Kata ini berasal dari Cīna bahasa Sanskerta, yang menyebar ke Cina melalui kitab-kitab agama Buddha dari India, yang kemudian terus menyebar ke Jepang juga bersama penyebaran Buddhisme. Nama itu dalam bahasa Jepang dilafalkan sebagai Shina. Sejak era Restorasi Meiji abad ke-18, orang Jepang menggunakan istilah Shina sebagai padanan nama “China” yang dipakai di Eropa.
Ini semula adalah kata yang netral, tidak ada makna negatif. Bahkan para tokoh nasionalis Cina awal abad ke-20 seperti Sun Yat-sen dan Song Jiaoren juga pernah menggunakan nama Zhina untuk menyebut negara mereka. Namun setelah nama Zhongguo diputuskan sebagai nama negeri, nama Zhina pun seketika ditinggalkan, dianggap sebagai pengaruh budaya asing.
Invasi Jepang ke Cina dalam Perang Dunia II membuat kata itu menjadi sangat negatif. Tewasnya jutaan orang Cina oleh kekejaman Jepang menimbulkan luka batin yang sangat mendalam di kalangan orang Cina, bahkan hingga hari ini. Mendengar nama Zhina/Shina, mereka akan teringat lagi akan trauma pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghinaan yang dilakukan oleh Jepang atas bangsa Cina. Karena itu, pasca Perang Dunia II, pemerintah Cina menuntut Jepang untuk mengganti penyebutan nama negara mereka dalam bahasa Jepang. Jepang pun akhirnya setuju untuk mengubah Shina menjadi Chuugoku, yang merupakan pelafalan bahasa Jepang dari 中国 (Zhongguo/Tiongkok).
Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia di bawah Presiden SBY menerbitkan keputusan untuk mengganti istilah “Cina” menjadi “Tiongkok” dan “Tionghoa”. Saya tidak tahu pasti apakah ada tuntutan resmi dari Beijing agar Indonesia melakukan hal itu. Namun yang jelas, pihak Indonesia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan seiring dengan “pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok”.
Pemerintah Cina sendiri selalu konsisten menggunakan nama “Tiongkok” dalam komunikasi resmi dengan Indonesia. Pada tahun 2010, saya pernah bekerja di China Radio International (CRI), stasiun radio multibahasa milik pemerintah Cina. Kami di divisi bahasa Indonesia harus selalu menggunakan istilah “Tiongkok” dalam siaran, sedangkan para kolega kami di divisi bahasa Malaysia tetap menggunakan istilah “Cina”. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Cina tidak mempersoalkan kata “Cina” itu sendiri, tetapi mereka tidak berkenan jika kata itu diucapkan oleh orang Indonesia. Itu karena adanya stigma negatif pada penggunaan kata itu dalam sejarah Indonesia, yang tidak terjadi di Malaysia.

Sekarang bagaimana kita menyikapi ini?
Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan dengan nama apa dia ingin dipanggil. Misalkan namamu Bagus, tetapi orang-orang memanggilmu Bagong dan kamu tidak suka, kamu berhak meminta mereka untuk mengoreksi cara mereka memanggilmu. Dalam konteks hubungan internasional, permintaan penggantian sebutan ini adalah hal yang cukup lazim dilakukan negara-negara di dunia. Misalnya, Indonesia juga pernah meminta media dan publik Malaysia untuk berhenti menyebut Indonesia sebagai “Indon”, yang dipandang sangat negatif oleh masyarakat Indonesia.
Dalam memanggil seseorang dengan nama tertentu, kita juga harus berempati terhadap perasaan orang itu terhadap panggilan yang kita gunakan. Misalkan kata Negro, semula hanya berarti “hitam”, merupakan kata yang netral dan objektif. Tetapi kemudian warna kulit hitam diidentikkan dengan perbudakan atau keterbelakangan, dan orang kulit hitam di Amerika Serikat mengalami diskriminasi yang di luar batas kemanusiaan, kata ini pun jadi punya stigma yang sangat negatif. Orang kulit hitam yang mendengar kata ini merasa sangat tersakiti. Karena itulah, demi menghormati orang kulit hitam, maka kata ini ditinggalkan dalam pemakaian sehari-hari di AS, diganti dengan istilah “orang Afrika-Amerika” yang lebih netral.
Di sisi lain, dari pihak yang dipanggil, adalah penting untuk menyadari bahwa yang membuat kita antipati terhadap sebuah nama bukanlah perkara nama itu sendiri, melainkan stigma negatif yang mengiringinya. Misalnya, kata “babi” di Indonesia menyiratkan makna kenajisan yang dilaknat Tuhan, sehingga panggilan “babi” menjadi hinaan yang luar biasa kasar. Namun di Cina, kata “babi” tidak senegatif itu maknanya, bahkan terkadang bisa menjadi panggilan kesayangan. Mengapa kata yang sama bisa membangkitkan emosi yang sangat berbeda? Bukan salah si “babi”, melainkan kitalah yang memberi stigma.

Karena itu, kita perlu memahami sejarah di balik nama-nama yang membangkitkan emosi tertentu dalam diri kita, untuk kemudian menyadari bahwa emosi itu muncul karena adanya stigma.
Saya pribadi telah menyaksikan perubahan yang spektakuler dalam kehidupan masyarakat Indonesia pasca Reformasi 1998, dengan jauh berkurangnya perlakuan diskriminatif dan kebencian rasial terhadap orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Saya tidak perlu lagi merasa malu untuk warna kulit saya atau mata sipit saya, tidak perlu merasa hina untuk menjadi Cina. Itu membuat saya tidak lagi merasakan stigma terhadap kata “Cina”, dan tidak lagi terlalu mempermasalahkan apakah orang menggunakan “Cina”, “China”, “Tiongkok”, atau “Tionghoa”.
Malahan jujur saja, belakangan ini saya lebih banyak menggunakan “Cina”, karena penggunaan “Tiongkok” dan “Tionghoa” dalam bahasa Indonesia sering membuat saya bingung: apakah masakan Tiongkok atau masukan Tionghoa? Bahasa Tiongkok atau bahasa Tionghoa? Tahun Baru Tiongkok atau Tahun Baru Tionghoa?
Tentu ini adalah sikap saya pribadi, dan saya tidak bisa mewakili semua orang Tionghoa di Indonesia. Saya tidak memungkiri masih banyak orang Tionghoa di Indonesia yang antipati dengan kata itu, dan saya menghormatinya. Tetapi bagi saya pribadi, sepanjang tidak ada stigma negatif, semua nama adalah sama baiknya. Lagi pula, apa gunanya kita memaksa orang untuk menyebut “Tiongkok”, tetapi orang itu tetap mengucapkannya dengan kebencian: “Dasar Tiongkok lo!”?
Sebagaimana dikatakan dalam kitab Tao Teh Ching: “Nama yang bisa dikatakan, bukanlah nama yang sejati.” Nama memang adalah identitas kita, tetapi nama bukanlah identitas kita yang sejati. Nama itu bisa berubah seiring tempat dan waktu. Nama yang sama pun, dalam konteks tempat, waktu, dan situasi berbeda, bisa punya makna yang berbeda pula.
Saat pergi ke Inggris dua tahun lalu, saya sempat terkejut mendapati orang-orang Inggris yang memeluk agama tua mereka dengan bangga menyebut diri, “Saya pagan!” atau “Saya penyihir!” Padahal, di Inggris Abad Pertengahan, seseorang bisa dibunuh dengan kejam apabila dituduh sebagai pagan atau penyihir. Mengapa mereka justru bisa mengadopsi nama-nama yang penuh makna penghinaan itu?
Seorang penganut pagan Inggris kemudian menjelaskan kepada saya, “Setiap nama itu punya daya sihir. Ketika seseorang menghinamu dengan semua nama dan kamu tersinggung, maka kamu sudah membiarkan daya sihir di balik nama itu untuk melukaimu. Tetapi sebaliknya, ketika kamu justru merangkul nama itu, menggunakannya dengan kebanggaan, maka kamu sudah mengalahkan daya sihir itu. Nama itu pun kehilangan kekuatannya, dan orang-orang juga tidak bisa lagi menggunakan nama itu untuk menyakitimu.”
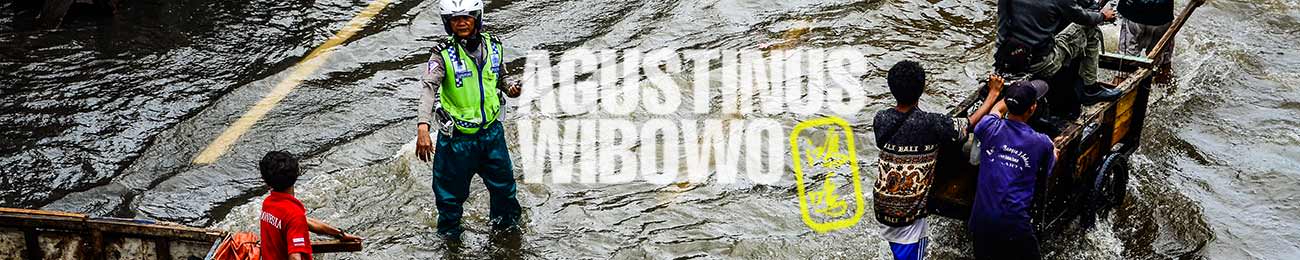





Saya jadi ingat seorang pedagang jajanan pasar di Malioboro yang pernah bercerita ke saya kalau dia sering dicemooh warga suruh pulang ke Cina. Padahal dia sendiri tidak pernah tau Cina seperti apa karena dia lahir di Indonesia sebagai peranakan Tionghoa. Rasanya sedih sampai sekarang kalau ingat waktu dicurhatin sama pedagang itu.
Mendengarkan Mas Agus menguraikan hal ini di Virtual Tour Imlek 2021 kemarin, mendadak saya teringat teman-teman sekolah saya. Besar, tumbuh dan banyak berteman dengan anak-anak/teman Tionghoa di sekolah Katholik, banyak mengajarkan saya tentang perbedaan. Meskipun saat itu saya minoritas di sekolah, sekitar hanya 10 orang pelajar muslim diantara ratusan lainnya, Romo (Kepala Sekolah) selalu meminta kami semua untuk saling menghormati dan tidak diperkenankan memanggil atau memberikan julukan kepada siapapun dengan menggunakan kata yang mungkin menyinggung hati.
Waktu itu, secara tersirat, semua paham untuk tidak memanggil teman-teman keturunan Cina dengan kata Hei Cina dan sejenisnya. Termasuk misal menggunakan kata Hei Batak kepada teman yang berasal dari Sumatera Utara. Jadi yang saya ambil dari kebijakan ini adalah pesan untuk saling menghormati dan tidak menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti hati.
trimakasih tulisannya koh agus.
Haha, saya termasuk golongan orang yang bingung dengan penggunaan nama cina/china atau tiongkok. Jadi tercerahkan oleh tulisan ini.
Saya sendiri tumbuh dalam interaksi yg terbatas dengan keturunan Cina (seringnya dilafal Cino oleh orang Jawa ya kan?). Saat kecil, saya hanya tahu orang2 Cina sbg juragan2 kaya. Setelah tinggal di kota lain baru saya mendapati kalau tidak semua Cina itu kaya.
Terima kasih koh Agus atas uraian diatas ttg saudara kami org Tionghua di Indonesia dan di daratan Tiongkok..iparku org Palembang she Lim mantuku org Pontianak she Pang.
Mantul mbak
oky
Salam. Aku setuju ambek pendapatmu gus.jeneng di ganti nek benci ambek wonge yo podo ae.