Selimut Debu 92: Peradaban yang Hilang
Hidup itu ada naik turunnya. Begitu Nassir Ahmad menyimpulkan perjalanan panjang dirinya. Demikian pula perjalanan peradaban bangsa Afghan. Sebuah negeri megah pernah berdiri di puncak kejayaannya, dan kini yang tersisa adalah debu-debu tanpa makna.
Terpana. Nyaris aku tak percaya menyaksikan ini. Di tengah kepungan gunung-gunung cadas dan tandus, tiba-tiba muncul sebuah menara menakjubkan—kemegahan yang muncul dalam kekosongan. Badannya kurus, menjulang setinggi 65 meter. Bentuknya yang tinggi ramping, sedikit doyong, namun justru memancarkan aura karena daya tahannya melintasi zaman ratusan tahun di tengah bebatuan cadas yang mengurungnya. Menara itu muncul tiba-tiba, tak terduga, tepat ketika Nassir Ahmad membelokkan mobilnya ke arah lembah. Siapa sangka di tempat terpencil seperti ini ada bangunan kuno yang berdiri dengan anggun? Siapa sangka setelah perang puluhan tahun yang menghancurkan Buddha raksasa Bamiyan dan gua-gua Buddha di seluruh penjuru negeri, minaret ini masih tegak tak terjamah?
Minaret Jam, dindingnya diselimuti ukiran ayat-ayat Al Quran dan puja-puji terhadap Sultan Ghiyasuddin, sang raja Dinasti Ghorid, yang menaklukkan kekuasaan Ghaznavi dan pada saat bersamaan mendirikan masjid kuno di Herat yang masih gemerlap dan agung hingga hari ini.
Lalu mengapa menara ini berdiri merana, sendirian di tempat sunyi ini? Di sekitarnya tak ada reruntuhan bangunan yang menemani. Kalau ia menara masjid, mana masjidnya? Kalau ia monumen lambang kebesaran Ghorid, mengapa harus di tengah gunung terpencil yang tak terlihat orang?
Baru-baru ini penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Minaret Jam adalah lokasi pusat peradaban yang hilang. Firuzkoh, yang artinya Gunung Pirus, adalah ibu kota kerajaan Ghorid. Konon kota ini adalah kota paling modern di zamannya, pusat peradaban Afghan dengan segala kerumitannya. Ketika pasukan Jenghis Khan menyerang, Firuzkoh hancur lebur.
Tapi sekarang tak ada yang tersisa. Firuzkoh menjadi misteri, orang tak tahu pasti di mana lokasinya. Ia bak Atlantis yang lenyap ditelan bumi. Apakah benar ibu kota Ghorid terletak di tempat Minaret Jam berdiri ini?
Aku memandang sekeliling. Sulit memercayainya. Tak ada sisa bangunan yang tertinggal. Ghorid adalah misteri. Dinasti besar yang lahir di tengah tebing cadas, bukannya dataran subur di tepi sungai yang dilintasi perdagangan. Tempat ini begitu terpencil, tetapi justru keterpencilanlah yang menyelamatkan Minaret Jam melintasi masa delapan abad tanpa banyak terjamah tangan manusia perusak atau kebodohan perang yang merobek-robek Afghanistan.
Tempat ini bakal segera jadi primadona wisata Afghanistan. Ada loket dengan papan pengumuman. Tiket untuk orang asing: US$5. Tiket parkir mobil: US$10. Tiket untuk naik menara: US$10. Hotel: US$30/malam (satu-satunya yang ada di daerah ini). Tapi tidak ada seorang pun yang menjual tiket. Mungkin petugasnya sudah terlalu bosan menunggu karena tidak ada satu pun turis yang datang.
Nassir sudah berteriak, ”Hai! Kamu mau balik ke Garmao atau tidak?” Di sini selain kami bertiga dan dua orang tentara, tak ada siapa-siapa lagi. Belum tentu pula ada kendaraan yang ke sini dalam tujuh hari ke depan. Aku tak punya pilihan selain melompat ke Mazda milik Nassir.
Minaret Jam kembali ke dalam kesendiriannya, seperti yang telah ia lewatkan selama delapan abad. Kami, manusia mungil yang hanya bisa kagum di hadapannya, tak lebih bagaikan bulir-bulir debu yang dibawa angin lalu. Selimut debu, selubung gunung, derai tangis, dan desing pertempuran, membungkus wajah Afghanistan yang sebenarnya—negeri kuno dengan peradaban agung yang terkubur.
”Kau lihat sendiri, Afghanistan bukan hanya debu dan perang. Kami pun punya kebudayaan tinggi. Sayang semuanya itu terkubur dalam berbagai gambar buruk tentang negeri ini. Sekarang semua orang bicara tentang Afghanistan, pasti yang terbayang adalah perang, perang, perang,” komentar Nassir.
Di tengah jalan, di bukit gundul, seorang kakek tua enam puluh tahunan menumpang kendaraan kami. Jenggotnya putih sempurna. Ia ingin ke Herat, tetapi Nassir hanya berjanji akan mengangkutnya sampai Garmao. Namanya Mohammad Yousuf, mengaku sudah bekerja lima puluh tahun di Iran. Meragukan. Sering kali penduduk desa Afghan punya konsep waktu yang berbeda dengan perhitungan normal. Yousuf berjalan kaki delapan jam dari desanya menuju Garmao.
Iran dulu pernah menghidupinya. Hingga kini pun negeri tetangga itu punya magnet yang kuat untuk menariknya kembali ke sana. Dia mengaku dulu pernah berjalan kaki dari rumahnya sampai ke Iran, sampai seribu kilometer. ”Aku sudah berjalan kaki keliling dunia. Sekarang siapa yang benar-benar pengelana dunia, kamu atau aku?” katanya.
Petualangan itu adalah masa lalunya. Sekarang ia sudah tua. Ia akan ke Iran dengan menggunakan paspor dan visa. ”Apa yang dulu ilegal, sekarang harus jadi legal. Apa yang sekarang legal, sebenarnya pun ilegal.” Kata-katanya sederhana, namun sebenarnya sangat filosofis. Dunia ini begitu nisbi. Konsep dan nilai yang menjadi standar hidup kita pun nisbi. Mana yang benar, mana yang salah, semua nisbi, tergantung dari siapa yang bicara, pemerintah mana yang membuat hukum, atau adat mana yang berlaku.
Yousuf menunjukkan visa Iran-nya. Ia buta huruf, ia tak tahu apakah ia masih bisa masuk Iran dengan visa ini. ”Ini sudah kedaluwarsa,” aku mengamati visa cokelat bergambar bunga-bunga indah itu, ”mesti ke kedutaan untuk minta visa baru lagi.”
”Aku harus cepat-cepat ke Iran,” katanya, ”Ini semua karena terpaksa. Aku tidak suka orang Iran. Mereka angkuh. Mereka memperlakukan orang Afghan seperti binatang kotor. Tetapi tinggal di sini pun sama tak enaknya. Kau lihat sendiri Ghor ini, tak ada apa-apa. Hidup susah. Ladang kami baru saja diserang tikus. Semua habis, bahkan buah-buahan pun tak ada yang bisa dimakan. Beras dan gandum semua harus dibeli dari luar, mahal sekali. Kami tak punya traktor, apa yang bisa kami hasilkan dari tanah berdebu ini?”
”Afghanistan, zindagi kheyli moshkel. Hidup di sini sangat susah,” berkali-kali Yousuf menyisipkan kalimat ini dalam keluh kesahnya.
Hidup memang susah, tetapi ia tetap harus berputar, selambat apa pun itu. Seperti Ghorid yang lahir di tengah angkuhnya pegunungan, membangun dinasti modern, lalu kembali tenggelam dalam misteri. Seperti Minaret Jam yang bertahan dalam kemeranaan ratusan tahun, menyaksikan musim berganti dengan khaak yang tak berhenti melintas diterpa angin gunung. Dan seperti gelombang penakluk dunia yang silih berganti menundukkan tanah gersang ini.
(bersambung)
Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Kerajaan yang hilang (AGUSTINUS WIBOWO)



4. Kehidupan di sini seperti tidak pernah berubah, dan tidak akan berubah (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Penantian yang tak pasti di kedai teh (AGUSTINUS WIBOWO)
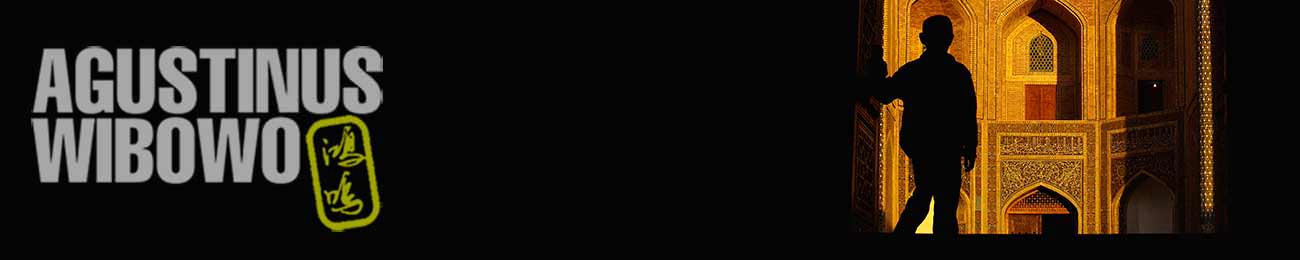





amazing…
gorgeous
jalan mnuju minaret eksotis. foto5: gambar bunga+poci gelas teh bisa jd pninggaln spt gbr2 di gua2 pninggaln manusia purba hmmmmm. kehidupan tidak akan berubah. dan memang tidak berubah
sungguh Afghaistan sebenarnya memiliki Peradaban yang LUAR BIASA. tapi perang telah menutupi dan merusak itu semua….. 🙂 Menyedihkan sekali…. Really… 🙂