Titik Nol 13: Danau Suci

Danau Suci Manasarovar. (AGUSTINUS WIBOWO)
Saya tercebur ke dalam sungai dari mata air Kailash. Sungai ini dalam dan arusnya kencang. Tubuh saya terseret terbawa arus.
Tangan pemuda itu dengan cekatan menangkap saya yang terjatuh dari batu. Basah kuyup saya menaiki batu-batuan ini. Tangan kanan saya dituntunnya. Sekali lagi saya terpeleset, nyaris hanyut. Tetapi bocah gembala ini tak hilang keseimbangannya.
Saya begitu berterima kasih ketika berhasil mencapai tepi sungai. Saya tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika hanyut sampai ke sungai besar di seberang sana. Kamera saya rusak. Paspor saya basah kuyup. Sekujur tubuh saya menggigil kedinginan. Tetapi saya harus maju.
“Darchen masih jauh,” kata bocah itu dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata.
Ia menunjukkan peta Kailash dari buku pelajarannya.
“Di sini sekarang kamu berada,” katanya menunjuk sebuah titik di sebelah barat lingkaran kora. Masih dua puluh kilometer lagi ke Darchen, dan hari sudah mulai beranjak senja.
Dengan perasaan hancur lebur, saya menyeret kaki saya yang sudah mulai lumpuh untuk terus maju. Tiga jam perjalanan yang dilewatkan dengan meringis kesakitan. Saya bersorak gembira ketika sampai di sebuah desa. Ada tiang penuh dengan bendera doa.
“Bukan. Ini bukan Darchen!” kata seorang turis Korea yang saya jumpai.
Darchen masih 13 kilometer lagi jauhnya. Ini adalah Kuil Zutulpuk, tempat di mana orang asing biasa berhenti di malam kedua. Kebanyakan turis melakukan kora dalam waktu tiga hari, sehingga mereka bisa menikmati keindahan Gunung Dewa perlahan-lahan.
Jam sudah menunjukkan pukul 19:30, dan saya masih harus mencapai Darchen sebelum gelap. Musim panas di Tibet sangat panjang. Matahari baru tenggelam pukul 10 malam, tetapi ini juga karena seluruh negeri China yang sebesar ini hanya punya satu zona waktu – waktu standar Beijing. Pukul 10 di Beijing seharusnya masih pukul delapan atau sembilan waktu informal Tibet.
Walaupun begitu, saya tetap tak boleh membuang waktu, karena saya tak mungkin meraba-raba jalan di tepi jurang ini waktu malam. Kalau tadi saya hanya menyeret kaki kiri, sekarang kaki kanan saya pun nyaris lumpuh. Dua-duanya harus diseret dengan tangan.
Maju, maju, dan terus maju. Hanya itu di benak saya. Seorang pria Tibet menyalip saya. Dia berjalan seperti terbang, tanpa henti.
“Darchen masih jauh, delapan kilometer lagi!”
Ketika langit mulai gelap, lolong anjing bersahut-sahutan, di kejauhan saya melihat sinar kerlap-kerlip. “Darchen!” saya menjerit. Ketika kedua lutut sudah terbujur kaku, ketika tangan pun lelah memaksa kaki untuk terus melangkah, ketika tenggorokan kering tak diisi setetes air pun, hati saya bersorak.
Betapa indahnya tujuan yang berkerlap-kelip di kejauhan sana. Betapa indahnya perkampungan itu setelah perjalanan panjang, mulai dari keindahan padang rumput, kebahagiaan melihat lukisan alam, hingga pendakian panjang yang menguras nafas, sampai tercebur dalam sungai deras. Betapa indahnya terang cahaya itu, dalam kegelapan malam, setelah perjalanan pencucian diri yang penuh derita.
Saya tergolek lemah di atas kasur keras.
“Kamu sungguh beruntung,” kata Xiao Wang pemilik warung di Darchen setelah mendengar kisah saya.
“Kamu tidak sampai masuk angin setelah tercebur sungai dingin itu. Kamu mesti ingat, jangan sampai masuk angin di tempat tinggi seperti ini. Kalau di bawah sana (dataran rendah) masuk angin cuma sakit biasa, di sini akibatnya bisa jadi kematian!” Xiao Wang bercerita tentang mahasiswa China yang berenang di Danau Suci, kemudian masuk angin, dan langsung mati hari itu juga.
“Di sini, masuk angin langsung jadi radang paru-paru!” terang Xiao lagi.
Yan Fang, yang berjalan jauh di depan saya, ternyata hanya mendahului saya sepuluh menit. Pasangan Korea Kim dan Seum malah belum sampai, mungkin mereka menginap di Kuil Zutulpuk. Ibu Polisi masih mencari mereka berdua.
“Awas nanti kalau ketangkap, pasti akan saya denda seberat-beratnya!” ujarnya gemas.
Selain kantor polisi, kampung penuh dengan toko dan rumah makan. Yang berdagang barang keagamaan adalah etnis Tibet. Orang China membuka restoran dan hotel. Yang datang ke sini kebanyakan para peziarah Tibet, turis lokal dan sedikit orang asing. Para peziarah Tibet datang dengan truk. Mereka yang benar-benar mengabdikan diri, datang dengan jalan kaki dari kampung mereka yang mungkin sampai ribuan kilometer jauhnya. Yang lebih hebat lagi, berjalan dengan merayap dan bersembah sepanjang jalan.
Sekarang Yan Fang, si gadis China itu, sudah berangkat mengayuh sepeda gunungnya melanjutkan perjalanan ke kota Lhasa yang seribuan kilometer jauhnya. Ia sungguh perempuan tangguh. Sedangkan saya, diajak serombongan turis dari Shanghai ke arah Danau Suci Manasarovar. Mereka datang jauh-jauh dari Lhasa dengan menyewa jip. Karena sudah bayar di muka, tak ada salahnya juga membawa saya turut serta.
Danau Manasarovar berwarna biru kelam, memantulkan tangkupan langit yang biru dengan awan berserakan. Airnya jernih, dingin, dan segar. Mandi dan berenang di sini sangat berbahaya. Tetapi orang Hindu yang datang dari India menjalankan ibadah ziarah dengan membasuh diri dalam danau.
Danau ini dalamnya sampai 90 meter, dan kelilingnya 90 kilometer. Airnya berasal dari Kailash, dan menghidupi banyak sungai suci dalam peradaban India. Sebut saja Sutlej, Brahmaputra, Indus, dan Gangga. Di tepi danau, di lereng bukit curam, berdiri Chiu Gompa, kuil Budha yang seperti diukir dari gunung batu itu. Barisan batu mani bertahta mantra menghadap ke arah danau dan Gunung Dewa. Biksu-biksu muda sibuk menghias dinding kuil kecil itu dengan gambar dan ukiran.
Seperti halnya Kailash, ibadah di Manasarovar juga dengan cara mengitarinya. Juga tidak mudah, sekali putaran butuh waktu sampai empat hari, harus berbasah-basah menyeberang jeram sungai yang deras. Orang Hindu India tak segan-segan mencelupkan diri dalam airnya yang basah, untuk pencucian dosa. Sulit membayangkan orang Budha Tibet yang mengitarinya sampai 13 kali. Turis biasanya mengitari danau ini cukup dengan duduk di dalam jip yang nyaman.
Di kejauhan nampak Kailash, dengan wajahnya yang tergurat garis lurus. Tak semua orang beruntung merasakan perjuangan perjalanan ini. Bahkan dengan kedua kaki yang masih belum bisa berdiri tegak, saya hanyut dalam kebahagiaan jiwa.
(Bersambung)
Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Titik Nol” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2013.
Dimuat di Kompas Cyber Media pada 20 Agustus 2008

Air danau ini membersihkan tubuh dari dosa (AGUSTINUS WIBOWO)

Sebuah dusun di tepi danau, dan Danau Setan tampak di kejauhan. (AGUSTINUS WIBOWO)

Kuil di tepi danau yang seperti terukir dari bukit terjal. (AGUSTINUS WIBOWO)
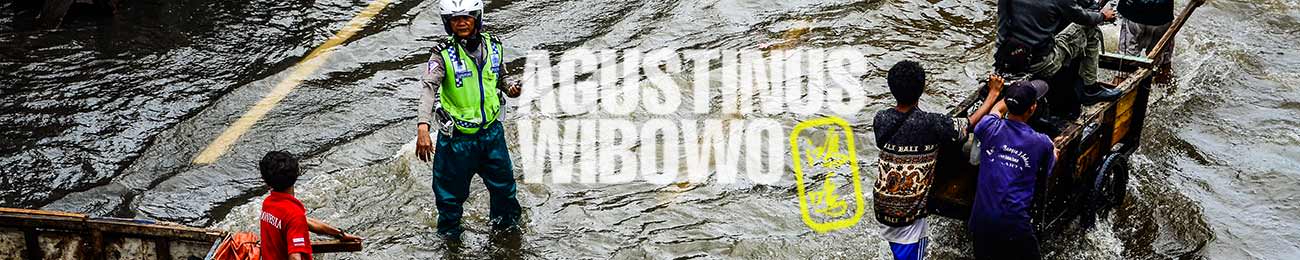





Gus … Like deh pokoknya 🙂
Terima kasih ya 😉
ema ikut bahagiaaa kaq baca ini….:)
Tambahin fotonya donk..biar imajinasi lebih seru… 😀