Selimut Debu 10: Makhluk Asing

Pemandangan pertama negeri Afghan (AGUSTINUS WIBOWO)
Detik-detik menuju Afghanistan semakin dekat.
Di ruang pemeriksaan paspor, setumpuk paspor hijau Korea Selatan tiba-tiba menyeruak, dibawa seorang pria yang kucurigai sebagai pemandu wisata. Di luar tampak beberapa pemuda dan pemudi Korea yang cekikikan, seperti sedang menyaksikan pertunjukan komedi. Tak kusangka, rombongan turis pun sudah sampai ke Afghanistan. Entah berapa lama lagi perjalanan ke Afghanistan masih layak disebut sebagai petualangan, sebelum negeri yang eksotik ini disulap menjadi taman hiburan Disneyland Edisi Zona Perang bagi turis-turis asing.
Adam dan aku melangkah menuju gerbang besar Afghanistan. Berbeda dengan Pakistan, tidak nampak tulisan “Welcome to Afghanistan” di sini. Atau mungkin saja ada, tapi dalam huruf Arab yang tidak bisa kubaca. Kami berjalan bersama seorang pria Afghan bertubuh subur, dengan bahasa Inggris yang fasih. Rupanya dia adalah penerjemah untuk kantor berita Fox.
“Kamu tahu, Fox itu memang persis seperti fox, mereka selicik rubah,” bisik Adam kepadaku, ketika pria itu tak hentinya menceritakan tentang pekerjaannya, kekayaannya, gajinya yang fantastis, … sungguh ironi dengan kemelaratan negara yang habis dihajar perang berpuluh-puluh tahun.
Memasuki Afghanistan, jarum jam seperti diputar mundur lima puluh tahun. Kekacauan yang balau, hiruk yang pikuk. Orang-orang berbondong-bondong menuju Pakistan, dengan barang-barang bawaan yang berbongkah-bongkah. Wanita-wanita berbalut burqa, ataupun wanita berkerudung yang duduk di keranjang beras, sedangkan suaminya mendorong dari belakang. Ada juga anak-anak kecil berlarian mengikuti orang tuanya. Semuanya tergesa-gesa menuju Pakistan. Semua berjalan terburu-buru, seakan dikejar-kejar sesuatu dari balik negeri Afghan sana.
Kacau yang balau. Aku tidak menemukan deskripsi lain yang lebih tepat untuk melukiskan border ini. Bahkan aku tak bisa melihat ada kantor pemeriksaan paspor untuk mengecap paspor. Ini perbatasan internasional atau perbatasan antar kampung? Setelah berjalan lebih kurang seratus meter, tiba-tiba kami disuiti beberapa orang berseragam tentara. Rupanya kantor pencatatan paspor berupa sebuah ruangan kecil berlantai tanah becek, dengan sebuah meja dan seorang petugas yang mencatat data-data paspor, tersembunyi di pinggir jalan berdebu. Sesudah dilihat-lihat sekilas dan data kami dicatat, kami disuruh meneruskan perjalanan lagi. Bahkan paspor kami pun masih belum dicap.
Kembali ke jalan, kembali melawan arus deras orang-orang yang berlarian menuju Pakistan. Sedangkan yang dari Pakistan menuju ke Afghanistan seperti kami tidaklah banyak. Puluhan pasang mata, dari orang-orang yang tidak sedang berbondong-bondong itu, lekat-lekat menatap kami. Mungkin mereka tidak sering melihat orang asing dengan memanggul ransel (spesies: Homo turisticus internationalis) yang melintas di sini. Pandangan-pandangan tajam dan misterius di hari pertama di sebuah negeri asing yang juga rawan, sungguh menggentarkan.
Lima puluh meter kemudian, kami disuiti orang lain lagi yang duduk di seberang kantor kontrol paspor. Ruang kontrol paspor ini, walaupun sedikit lebih nyaman, tidak jauh lebih mewah daripada ruang pencatatan paspor yang tadi. Seorang pria gemuk berjubah putih mencatat data-data paspor kami, kemudian membubuhkan cap masuk dengan tanggal yang ditulis tangan. Cap itu, hijau tipis warnanya, semuanya dalam huruf Arab, samar-samar tertera dalam lembar pasporku. Nampaknya hanya orang asing saja yang perlu untuk mengecapkan paspor di sini. Karena wajah kami yang jelas bukan wajah lokal, kami jadi sering disuiti untuk pemeriksaan paspor. Kalau saja wajahku lebih mirip orang Afghan, aku bahkan bisa masuk tanpa menunjukkan dokumen apa pun. Orang bilang, zaman Taliban dulu tidak perlu visa atau paspor untuk masuk Afghanistan, cukup punya jenggot lebat, plus kerudung atau jubah. Menyelundup ke Afghanistan itu tidak susah-susah amat, Kawan. Mau coba?
Pria gendut penerjemah Fox itu menawarkan kami ikut dengan mobil mereka. Aku sempat gembira, kukira bisa menumpang gratis.
“One hundred bucks only,” katanya.
Seratus… dolar? Saja? Hanya untuk dari Torkham ke Kabul yang cuma seratusan kilometer? Seratus dolar! Baginya yang pakai uang kantor, ini cuma angka kecil. Justru kebiasaan bagi-bagi duit para pegawai perusahaan internasional inilah yang menyebabkan Afghanistan sangat mahal. Apalagi buat orang asing, orang lokal mengira orang asing semua sama kayanya.
Pertama-tama, kami harus menukar uang, setidaknya cukup untuk ongkos perjalanan menuju Kabul. Berbeda dengan di Pakistan, Afghanistan sangat tidak terbiasa menerima kedatangan turis. Kehadiran kami berdua langsung menarik perhatian setidaknya puluhan pria yang mendekat, mengelilingi kami seakan-akan kami adalah makhluk aneh dari planet Mars. Bisik-bisik, desas-desus, teriakan-teriakan, serta tawa-tawa sangar, aku sungguh tak tahu apa yang mereka bicarakan dan pikirkan. Dan perasaan tidak bisa mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi di negeri yang begini berbahaya membuat aku panik.
Saat aku menukarkan dolar menjadi lembaran-lembaran uang Afghani, jumlah para penontonku dan ekspresi-ekspresi takjub mereka tidak kalah dengan jumlah dan ekspresi orang-orang desa di kampungku saat TVRI melakukan syuting saat aku masih kecil dulu.
Walaupun puluhan pasang mata yang menatapku begitu misterius, setidaknya aku bisa mengatakan: “Ah, inikah rasanya jadi pusat perhatian, jadi selebritis itu?”
(bersambung)
Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

Berbondong meninggalkan Afghanistan, menuju Pakistan (AGUSTINUS WIBOWO)

“Hati-hati Ranjau!” pesan dari OMAR (AGUSTINUS WIBOWO)

Pelat mobil bertuliskan angka Arab (AGUSTINUS WIBOWO)

Di sini visa Afghanistan diteliti dan distempel (AGUSTINUS WIBOWO)

Perang dan pengungsi adalah pasangan serasi (AGUSTINUS WIBOWO)

Para petugas keamanan perbatasan Afghanistan (AGUSTINUS WIBOWO)
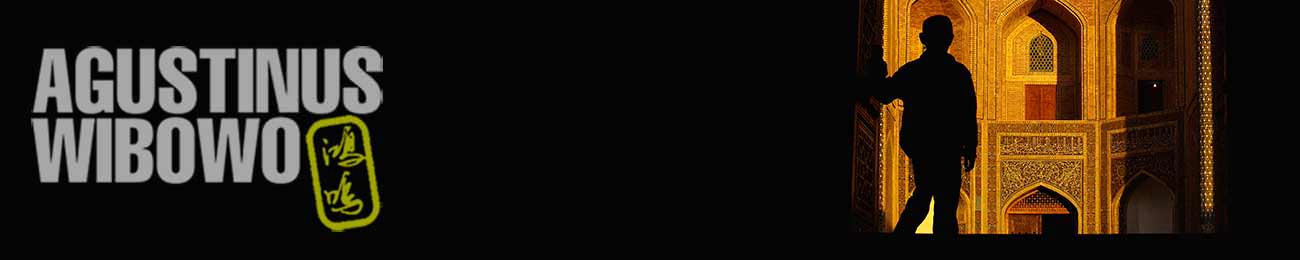





yes, you are a celebrity ..
semoga afghanistan tidak menjadi tempat “wisata perang” bagi turis2 yg cuma ingin menguji adrenalin
Homo turisticus internationalis??? hehehe….