Titik Nol 20: Perayaan Akbar

Pengibaran bendera Republik Rakyat China di depan Potala. (AGUSTINUS WIBOWO)
Bendera merah dengan lima bintang emas berkibar di seluruh penjuru Lhasa. Provinsi ini sedang bersolek merayakan empat puluh tahun berdirinya Tibet Autonomous Region (T.A.R), empat puluh tahun yang merombak total wajah dan kehidupannya.
Di hadapan Istana Potala, bendera besar berwarna merah berkibar gagah. Lagu kebangsaan China, “Bangkitlah…. orang-orang yang tak hendak menjadi budak ….” membahana. Barisan tentara berseragam hijau memainkan terompet, seruling, genderang. Yang lainnya melakukan gladiresik, menyambut upacara perayaan akbar yang akan berlangsung di lapangan di depan Potala.
Pada tahun 1951, utusan pemerintahan Tibet di bawah Dalai Lama menandatangani perjanjian dengan pemerintah komunis di Beijing. Tibet, walaupun punya pemerintahan sendiri, tak pernah diakui oleh negara mana pun sebagai negeri berdaulat. Salah satu poin perjanjian itu adalah menyatakan Tibet adalah bagian dari Republik Rakyat China dengan otonomi. Peristiwa bersejarah itu dirayakan sebagai terbebasnya Tibet, kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Tahun-tahun berikutnya, kedudukan Dalai Lama sebagai pemimpin spiritual sekaligus dewa di hati orang Tibet, secara perlahan namun pasti, mulai tergeser, hingga pada akhirnya sang pemimpin melarikan diri ke India tahun 1959. Tanggal 1 September 1965, berdirilah Daerah Otonomi Tibet (T.A.R) dengan wilayah yang jauh lebih kecil daripada teritorial Tibet di bawah pimpinan Dalai Lama. Tibet yang dulunya terdiri atas Ü-Tsang, Amdo, dan Kham, kini hanya tersisa Ü-Tsang dan bagian barat Kham saja.
Tibet melewati masa-masa sulit bersama kegilaan Revolusi Kebudayaan yang melanda seluruh penjuru China. Kuil-kuil dirusak, biksu ditangkap dan gulungan sutra dihancurkan. Adat kuno, kepercayaan, feodalisme, dibasmi sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya Tibet yang luluh lantak, semua provinsi, kota, desa, sampai kampung di negeri ini mengalami nasib yang sama.
“China memang berhutang kepada seluruh penduduknya, terutama bangsa minoritas, tetapi Tibet sebenarnya adalah anak kesayangan China.” kata Li, namanya terpaksa disamarkan, seorang pemuda dua puluh tahunan asal Sichuan.
Setelah keadaan nasional mulai stabil, pemerintah pusat mengucurkan dana besar untuk pembangunan daerah-daerah di bagian barat negeri yang tertinggal. Tibet salah satunya yang mendapat perhatian paling besar. Pembangunan di tempat terpencil di atap dunia ini sangat gencar.
Jalan raya mulus menghubungkan Tibet dengan provinsi-provinsi tetangga, melepaskan isolasinya. Gedung-gedung tinggi di kota Lhasa juga menunjukkan betapa pesatnya perubahan itu. Sekolah, rumah sakit, toko, bermunculan di seluruh penjuru. Investasi juga menggila.
Para pedagang dan pebisnis berdatangan dari Sichuan, Xinjiang, dan provinsi lainnya. Turisme pun mulai menggeliat. Tibet, perlahan-lahan bukan lagi dunia Shangrila yang tersembunyi di ujung dunia. Tibet sudah terhubung dengan alam normal, terjamah globalisasi dan modernisasi.
“Adalah ibu pertiwi yang membebaskan Tibet dari feodalisme. Dulu, di bawah Dalai Lama, perbudakan merajela. Tibet sangat feodal. Yang berkuasa adalah para lama dan pejabat tinggi, memperbudak rakyat miskin di mana-mana. Agama menjadi alat kekuasaan, bahkan lama pun bersenjata,” kata Xiao Yang, seorang mahasiswi Universitas Peking.
“Gadis dikawinkan dengan tiga pria kakak-beradik sekaligus. Satu laki-laki mengawini beberapa perempuan. Mereka tak berpikir lain-lain lagi, selain sembahyang dan mendewakan Dalai Lama berlebihan. Sekarang kamu lihat, pembangunan telah mengubah banyak kehidupan di sini. Orang Tibet tidak lagi terbelakang. Mereka berpendidikan, dan tempat ini pun maju,” lanjut dia lagi.
Xiao Yang tak mengada-ada. Tibet sudah banyak berubah, walaupun kebiasaan poliandri masih berlaku di desa-desa. Pemerintah China sekarang sedang giat membangun, salah satunya adalah jalur kereta api Qinghai Tibet (Qing-zang Tielu), rel kereta api tertinggi di dunia yang melintasi barisan gunung tinggi di puncak bumi. Mukjizat dari kemajuan teknologi modern ini akan semakin membuat Tibet terekspos pada kemakmuran dan modernisasi. Lebih banyak lagi barang dan manusia yang akan mengalir ke tempat yang dulunya terkucil ini.
Saya hanya seorang pengunjung yang melihat sekilas, tetapi saya merasakan ada dinding tak terlihat yang memisahkan orang Tibet dengan kaum pendatang etnis Han dan Uyghur. Ada rasa curiga. Bahkan kepada saya, orang asing yang sering diasumsikan sebagai orang Han.
Orang Tibet hidup dalam dunia mereka sendiri – dunia spiritual mereka, pemujaan dan ritual mereka, kosmologi mereka sendiri. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga besar untuk ziarah ke tempat-tempat suci, dari pagi sampai malam hanya memutar roda doa dan tasbih, melantunkan doa tanpa henti. Dengan penuh kekhusyukan, orang Tibet tradisional terseok mengelilingi Lapangan Barkhor, bersujud di hadapan Potala dan Kuil Jokhang, menempelkan dahi di bendera suci, terperangkap dalam kepercayaan mistis mereka.
Suku pendatang, sebaliknya, sibuk meraup keuntungan di tempat yang sedang berkembang pesat ini. Toko-toko modern berjajar sepanjang jalan utama di Lhasa. Huruf Mandarin mendominasi pemandangan ibu kota. Tempat-tempat suci juga menjadi tempat berbisnis, menjual dagangan dan mengeruk keuntungan. Keberhasilan pembangunan, kemajuan ekonomi, peningkatan kecerdasan yang menjadi tolok ukur kesuksesan hidup.
Orang Tibet tidak melebur dengan etnik pendatang. Bahasa adalah salah satu kendala, kebanyakan orang Tibet tak bisa bahasa Mandarin. Tetapi saya tidak bicara bahasa di sini. Suku-suku minoritas di Yunnan juga banyak yang tak bisa berbahasa Mandarin, tetapi mereka merasa ikut memiliki identitas sebagai bangsa China. Di Tibet, semua itu terpendam dalam hati yang terdalam.
“Tibet,” kata Li, “ibaratnya adalah anak tiri. Pemerintah China berusaha merebut hatinya, menghujaninya dengan hadiah pembangunan, kemajuan ekonomi, jalan tol, listrik, modernisasi. Tetapi si anak tiri tak tergerak hatinya.”
Ini mungkin bukan ucapannya sendiri, mungkin kutipan dari orang lain, karena saya sepertinya sudah pernah mendengar perumpamaan ini sebelumnya.
Lapangan di hadapan Potala semakin semarak. Pasukan tentara pemusik yang memainkan lagu kebangsaan menyedot perhatian banyak orang. Puluhan orang Tibet berkerumun di hadapan panggung hiburan, penasaran akan perayaan akbar yang akan berlangsung minggu depan. Celana jins, kaus ketat, rompi, sepatu kets, rok panjang, berpadu dengan celemek kotak-kotak, tasbih, dan roda doa. Modernisasi dan tradisi berharmoni.
Enam puluh lima tahun silam, di tempat kami berdiri ini, yang ada hanya jalan tanah, pengemis kelaparan, ratusan peziarah yang berserah diri sepenuhnya sambil merangkak ke arah Potala, dan orang-orang yang kostumnya sekarang sudah musnah dari peredaran.
(Bersambung)
Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Titik Nol” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2013.
Dimuat di Kompas Cyber Media pada 29 Agustus 2008

Di bawah kibaran bendera merah. (AGUSTINUS WIBOWO)

Jalur lingkhor keliling Potala yang sudah dipermak menjadi taman dan kolam. (AGUSTINUS WIBOWO)

Wajah kota Lhasa hari ini. (AGUSTINUS WIBOWO)
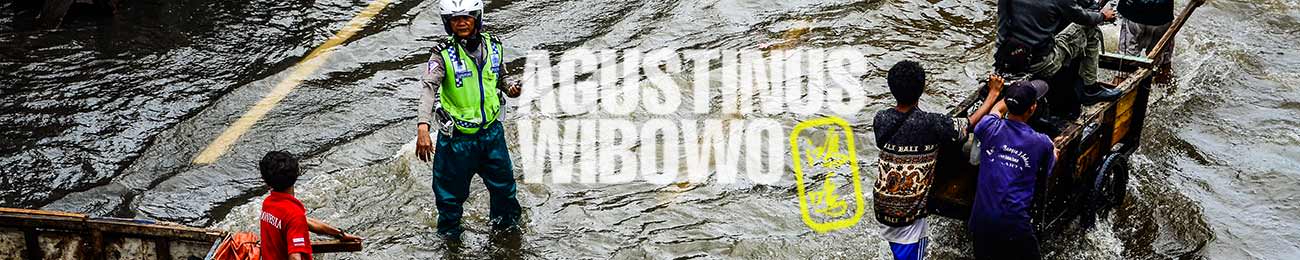





tks mas. Jadi ingat lagi buku titik nol