Titik Nol 187: Minoritas

Umat Nasrani melaksanakan misa di girjah – tempat berjatuh (AGUSTINUS WIBOWO)
Minggu, 28 Oktober 2001, pukul 9 pagi kurang sedikit, jemaat Kristen Protestan baru saja mengakhiri kebaktian. Bapak pendeta melangkah keluar, diikuti oleh umatnya yang berbaris untuk bersalaman dan menerima pemberkatan.
Tiba-tiba, dua orang tak dikenal menyergap melalui pintu gerbang. Mereka memuntahkan peluru dari bedil otomatis. Mayat bergelimpangan. Darah mengalir di mana-mana. Enam belas orang meregang nyawa.
Ini terjadi di Bahawalpur di jantung propinsi Punjab. Teror berdarah pertama yang ditujukan bagi minoritas Kristen sejak puluhan tahun silam. Namun ini bukan yang terakhir. Hingga saat ini, umat Nasrani di kota ini masih dicekam ketakutan dan trauma.
Gereja Katolik Santo Dominic, terletak di pusat kota Bahawalpur, langsung menjadi sorotan dunia. Dulu umat Protestan juga beribadah di sini, tetapi setelah tragedi itu mereka menggunakan gereja sendiri. Setiap misa di Gereja Santo Dominic juga dikawal polisi bersenjata, untuk menghindari serangan lainnya.
Saya sangat tercengang melihat interior gereja ini. Sangat sederhana. Hanya ada tiga bangku panjang di kanan untuk laki-laki dan tiga lainnya di kiri untuk jemaat perempuan. Tempat yang disediakan bagi sebagian besar jemaat adalah permadani yang terhampar. Jemaat beribadah dengan bertekuk di atas lutut, menjatuhkan diri di hadapan Tuhan. Ini sesuai dengan arti harafiah kata gereja dalam bahasa Urdu, girjah, tempat (jah) berjatuh (gir).
Lantunan lagu rohani Katolik yang berat dan khidmat mengiringi iring-iringan pastor yang akan memimpin misa. Semua umat berdiri takzim. Yang laki-laki hampir semuanya mengenakan shalwar kamiz. Yang perempuan berkerudung dan berjilbab. Khotbah disampaikan dalam bahasa Urdu. Seperti umat Muslim, umat Kristen menyebut Tuhan sebagai Khuda. Tetabuhan kendang dan harmonium yang biasa mengiringi qawwali – musik religius Sufi – menggemakan kebesaran Tuhan.

Pastor Nadeem (AGUSTINUS WIBOWO)
Ruangan Pastor Nadeem Joseph, merangkap sebagai kepala sekolah di sini, dihiasi gambar-gambar Muhammad Ali Jinnah – Bapak Pendiri Pakistan, Yesus Kristus, dan Bunda Maria. Kipas angin tua berderik ketika baling-balingnya menghamburkan panasnya bulan Mei yang menyengat.
“Semuanya gara-gara Amerika,” kata Pastor Nadeem mengawali kisahnya, “serangan Amerika ke Afghanistan untuk membalas kejadian 11 September 2001 membangkitkan kemarahan di Pakistan. Tetapi justru kamilah yang menjadi sasaran kemarahan itu.”
Di hari naas itu, delapan orang berkomplot melakukan pembantaian di gereja ini. Ada yang mengintai di luar, ada yang berjaga di halaman, ada yang menerjang masuk. Pelaku yang berhasil ditangkap mengungkap bahwa mereka ingin memberi ‘pelajaran’ kepada Bush dengan menyerang gereja.
“Kami ini selalu dianggap orang asing di Pakistan walaupun kami semua adalah warga negara ini,” keluh Pastor, “Bukan hanya kejadian ini saja. Terlalu banyak hukum yang diskriminatif atas dasar perbedaan agama. Kami tidak memilik kebebasan. Kalau bukan pemerintah kami sendiri yang melindungi kami, lalu siapa lagi?”
Hingga hari ini, gereja selalu sepi jemaat.
Umat Kristen di Pakistan berjumlah lebih dari dua juta jiwa. Komposisi Protestan dan Katolik hampir sama. Sejak kejadian penembakan di Bahawalpur yang langsung menjadi sorotan dunia, rentetan serangan terhadap umat Nasrani semakin tinggi frekuensinya, seringkali karena provokasi. Berita terakhir yang saya baca adalah tentang kerusuhan besar di Sangla Hill yang melibatkan ribuan orang merusak semua gereja di kota itu, hanya karena beredar rumor seseorang menyobek Qur’an.
Saya merasakan trauma dan keputusasaan ketika mengunjungi perkampungan kumuh Bhatta 2, yang mayoritas dihuni umat Kristen. Di negeri ini, umat Nasrani identik dengan perkampungan kumuh dan pekerjaan ‘rendah’ seperti tukang sapu atau pembersih jalan.
Mengapa umat Kristen di sini sangat miskin walaupun umumnya kualitas pendidikan di sekolah Kristen sangat bagus? Aidin, seorang kawan Muslim, menduga bahwa keterbelakangan ini gara-gara kebiasaan umat Kristen minum minuman keras. Bukan hanya minum, orang Kristen juga memproduksi dan berdagang arak. Satu kantung kecil harganya seratus Rupee, dibuat sembunyi-sembunyi di balik tembok rumah sederhana di perkampungan kumuh ini.

Orang Kristen yang bekerja sebagai pembersih gorong-gorong. Bagi kaum minoritas ini, mencari pekerjaan yang layak sangat susah. (AGUSTINUS WIBOWO)
Pervez Masih, pria Kristen berusia 34 tahun, mengantar saya berkeliling perkampungan. Rumah buruk rupa berbaris rapi sepanjang jalan lurus. Bau teramat busuk menyebar dari genangan air pekat yang berasal dari selokan yang buntu. Sampah berserakan di jalan.
“Sudah ratusan jurnalis asing datang ke tempat ini,” kata Pervez, “apalagi sejak jatuhnya pesawat Presiden Zia-ul-Haq di bukit belakang sana.”
Presiden Zia, menggantikan Zulfiqar Ali Bhutto melalui kudeta dan menggantungnya, kemudian menerapkan Shariah ketat di Pakistan, tewas dalam kecelakaan itu. Tak jauh dari perkampungan ada tanah makam. Di sini banyak kuburan kuno yang usianya lebih dari 200 tahun, termasuk makam misionaris Eropa yang membawa agama Kristen ke sini.
“Dua ratus tahun lalu,” lanjut Pervez, “seluruh daerah ini adalah hutan lebat yang tidak dihuni manusia. Baru sekitar 40 hingga 50 tahun semua orang di kompleks ini menganut agama Kristen.”
Pervez membawa saya mengunjungi sebuah gereja Katolik di dalam perkampungan. Kosong melompong. Tak ada bangku sama sekali. Altarnya cuma meja berbalut taplak putih, dihiasi salib kecil, dan sebuah gambar Maryam. Anak-anak kecil berkalung salib berebutan minta difoto dalam gereja.

Sebuah keluarga Nasrani di kampung miskin Bhatta 2 (AGUSTINUS WIBOWO)
Pervez sendiri jarang beribadah ke gereja lagi sejak pembantaian masal itu. Alasannya takut. Sekarang Pervez juga menjual arak untuk menyambung hidup.
“Mari minum,” ia menawarkan segelas cairan alkohol bening tanpa sungkan.
Kaum marginal yang didera diskriminasi, trauma, teror, kemiskinan, dan alkohol, semakin dalam terperosok dalam keterpurukan. Entah kapan mereka bisa bangkit lagi menggapai cita-cita yang diemban para misionaris itu.
(Bersambung)
Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Titik Nol” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2013.
Dimuat di Kompas Cyber Media pada 23 April 2009
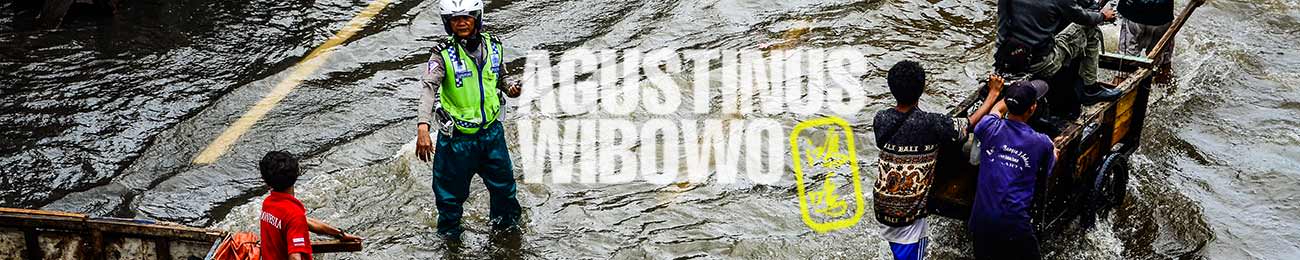





Leave a comment