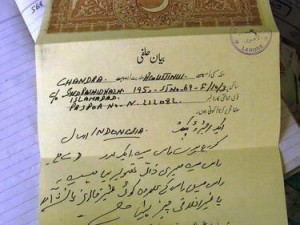Digo 24 Oktober 2014: Sekolah Papua Nugini di Indonesia
Pagi yang dingin, sekujur punggung saya pegal karena semalaman tidur di atas bilah kayu lantai gubuk yang renggang-renggang. Saya terbangun oleh sayup-sayup suara anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Papua Nugini dengan nada sumbang di kejauhan. O arise all you sons of this land, Let us sing of our joy to be free, Praising God and rejoicing to be Papua New Guinea. Saya sedang berada di Digo, sebuah kamp yang dihuni para pengungsi OPM (Organisasi Papua Merdeka) dari wilayah Papua Indonesia yang melarikan diri ke wilayah Papua Nugini pada tahun 1984. Tetapi banyak penduduk sini yang tidak menyadari bahwa Digo sebenarnya berada di wilayah Indonesia, bukan di Papua Nugini. Letak Digo adalah sekitar 5 kilometer di barat garis perbatasan lurus antara kedua negara. Bagaimana lagu kebangsaan Papua Nugini bisa dinyanyikan di wilayah Indonesia? Saya bergegas menuruni tangga rumah panggung, berlari menuju gedung sekolah. Di kamp pengungsi ini, semua dari 40an rumah panggung yang ada terbuat dari bahan-bahan hutan, yaitu kayu, kulit pohon sagu, dan daun sagu, sedangkan sekolah yang terletak di tengah lapangan bertanah merah itu dindingnya terbuat dari seng. Seng—yang bahannya harus dibeli dari pasar di kota, minimal dua hari perjalanan dari sini—sudah terbilang sangat mewah untuk kehidupan [...]